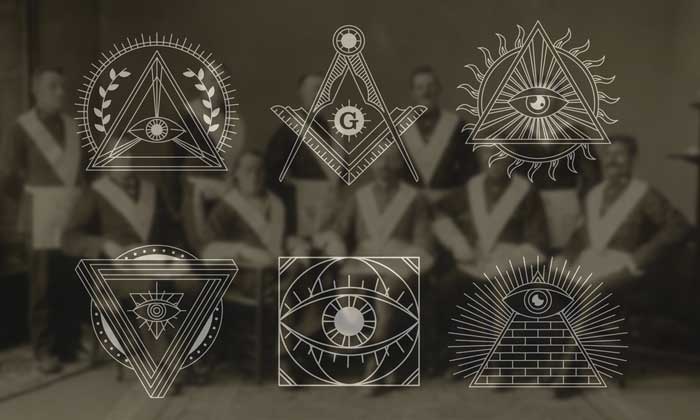Seandainya sebagian besar manajemen perusahaan memiliki CSR (Corporate Social Responsibility) yang kuat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, mungkin berbagai problem mendasar bangsa ini seperti kemiskinan dan pengangguran akan relatif teratasi.
CSR untuk Pemberdayaan Masyarakat
Bentuk CSR apa saja, tetapi yang prioritas mungkin disesuaikan dengan problem-problem kebanyakan masyarakat Indonesia seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan lain-lain. Tetapi memang masalahnya tidak semua kebijakan sosial perusahaan lingkage dengan problem-problem mendasar tadi.
Banyak program-program “CSR” yang bersifat artifisial, bias, dan belum tentu cocok dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu ada orientasi yang kuat di kalangan pengambil kebijakan perusahaan atau pemegang policy CSR supaya pandai membaca trend dan kebutuhan masyarakat. Perlu ada assesment untuk itu, jangan sekedar buang-buang uang ke masyarakat tetapi tidak meninggalkan dampak apa pun.
Peluang perusahaan turut serta dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil aangat potensial karena perusahaan adalah value creator. Mereka punya dana, punya SDM, punya teknologi.
Seandainya sebagian besar manajemen perusahaan memiliki visi yang kuat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, mungkin berbagai problem mendasar bangsa ini seperti kemiskinan dan pengangguran akan relatif teratasi.
Program Kemitraan yang diwajibkan kepada setiap perusahaan BUMN agar men-spend 1 s/d 3 % dari laba bersih untuk mendukung UKM dan Koperasi, misalnya, perlu dijadikan role model. Tentu saja dengan mempelajari berbagai kelemahan yang ada.
Kita bisa bayangkan, jika di Indonesia ini ada sekitar 150-an perusahaan BUMN besar dan kecil, dan semuanya diwajibkan menyisihkan dana kemitraan sebesar 1 s/d 3% dari laba bersih, tak terbayangkan berapa besar dana yang bisa terkumpul? Belum lagi dana-dana sosial yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta.
Tapi sekali lagi, “gerakan” untuk menjadikan praktik CSR perusahaan ini menjadi sesuatu yang sinergis belumlah ada. Semuanya berjalan parsialis, tergantung masing-masing. Bahkan, jarang sekali perusahaan yang memiliki blue print kebijakan sosial. Ini sangat disayangkan karena jatuhnya seperti bagi-bagi uang saja. Sementara impaknya nggak ada.
Perusahaan dengan CSR (Corporate Social Responsibility) yang berkesinambungan bisa turut menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran, asalkan manajemen perusahaan memiliki visi yang kuat terhadap masalah-masalah sosial.
Lebih dari itu, program-program yang dimunculkan dari praktik CSR haruslah program yang diarahkan untuk menyelesaikan akar masalah, “tackling the root of causes.” Bukan sekedar program bagi-bagi uang, sekedar memoles citra perusahaan dan mengamankan bisnis semata-mata. Kalau programnya semacam ini, sampai kapan pun praktik CSR tidak akan pernah efektif.
Sebenarnya, CSR sudah cukup diterima masyarakat Indonesia. Bukan rahasia lagi bahwa di dalam benak masyarakat tertanam bahwa perusahaan adalah pemilik modal, mereka berbisnis; dan untuk itu perusahaan harus share keuntungan dia untuk masyarakat.
Dari yang sepele, misalnya perusahaan dimintain sumbangan 17-an, sponsor kegiatan mahasiswa, pembangunan masjid, dan sebagainya. Praktik semacam ini telah tumbuh lama bahkan sejak sebelum istilah CSR itu sendiri muncul. Hanya sekarang kan variasinya sudah sangat kompleks dan beragam, ditujukan pada pemberdayaan komunitas yang lebih signifikan.
Per teori, orang pun lalu mengaitkan CSR dengan praktik bisnis perusahaan yang sangat masif, eksploitatif, dan ekstraktif yang mempengaruhi keseimbangan alam dan sosial. Sehingga bisnis harus bertanggungjawab terhadap perubahan keseimbangan tersebut sebagai ekses dari praktik bisnis yang dilakukannya, ini yang kemudian dikonseptualisasikan dengan tanggung jawab sosial perusahaan bisnis atau CSR.
Tetapi, bagi sebagian kalangan perusahaan, mereka tidak happy dengan CSR. Mereka berpandangan bahwa tanggung jawab sosial bukanlah urusan bisnis, melainkan pemerintah. Mereka berprinsip, “the business of business is business.”
Faktanya, wacana berbisnis secara etis dan harus bertanggungjawab secara sosial dewasa ini lebih diterima sebagai mainstream, dan telah pula diadopsi oleh manajemen bisnis modern. Jadi, secara umum, boleh dikatakan bahwa CSR relatif telah diterima oleh masyarakat, pun oleh masyarakat bisnis itu sendiri.
Paradigma CSR itu sendiri ada yang berpendapat bahwa CSR itu bersifat “voluntary” atau kerelaan. Oleh karena itu dia bersifat mana suka, dan disilakan kepada institusi bisnis untuk mengadopsi konsep ini ataukah tidak. Tetapi, sebaliknya, ada yang berpandangan bahwa CSR haruslah bersifat “mandatory,” menjadi bagian dari mandat dunia bisnis itu sendiri.
Begitu seseorang memutuskan berbisnis atau mendirikan perusahaan, maka secara intrinsik dengan sendirinya tanggung jawab sosial itu melekat dalam praktik bisnisnya. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk menegakkan praktik bisnis yang beretika dan bertanggungjawab secara sosial ini penting dilakukan.
Tetapi memang, kedua paradigma ini sama kuat. Di perdebatan internasional, misalnya dalam pembahasan ISO 26000 yang akan diluncurkan pada tahun 2008 yang akan datang, dipakai “kata tengah” untuk mengakomodasi dua kutub pemikiran ini, sehingga ISO mengenai tanggung jawab sosial ini pun unik.
Berbeda dengan produk ISO lain yang bersifat pengaturan atau standar, ISO 26000 disebut sebagai Guidance on Social Responsibility. Jadi hanya sekedar panduan atau ‘guidance’ bukan bersifat standard, karena memang ternyata susah sekali untuk menemukan titik temu perlunya pengaturan atau tidak terhadap CSR ini.
Namun dengan (sekedar) sebutan panduan pun sudah lebih dari cukup untuk menisbatkan bahwa wacana tentang tanggungjawab sosial ini –khususnya bagi dunia bisnis, akan semakin boom ke depan. Suka atau tidak, ia akan menjadi sandaran penting bagi dunia bisnis ke depan; bahwa berbisnis itu haruslah dengan etika. Dan salah satu dimensi dari etika bisnis tersebut adalah perlunya mereka bertanggungjawab secara sosial (socially responsible).
CSR untuk Pemberdayaan Masyarakat